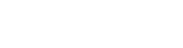Karya : Kezia Karen Hapukh Hutagalung
[ NIM : 2241210013 ]
Persembahan untuk Wuhan, China. Klik! Kutarik pelatuknya, setelah menarik napas — mengakhiri lamunanku malam itu.
Di tengah suhu 23° Celsius, aku terduduk beralaskan lantai di tepi jendela kamarku, menatap secarik surat dan tinta yang berbaris rapi, ditemani secuil ketabahan untuk menghangatkan tulang-tulangku— selagi aku membaca apa-apa yang tersisa setelah ‘Genosida Wuhan’ setahun yang lalu.
Suatu hari, aku merasa dunia ini begitu penuh dengan warna. Aku percaya, warna-warna itu berkelip-kelip dalam sinar, dan meski malam datang, tak ada kegelapan yang benar-benar meniadakannya. Aku yakin dunia ini lebih dari sekadar merah, ada maroon yang hangat, lebih dari biru, ada navy yang gelap. Lebih dari oranye, ada warna oren persija yang membara, ada oren es orson yang menenangkan. Sebelum aku benar-benar merasakan kehilangan, aku begitu yakin bahwa tak ada kekosongan yang abadi. Pasti akan ada kepingan puzzle entah dari mana yang akan melengkapinya. Pasti ada … pasti.
Tapi kemudian hidupku terhenti sejenak saat kabar duka menyergap—aku dan Bapakku dinyatakan positif terjangkit virus corona. Isolasi mandiri menjadi takdir sementara, menjauhkan kami dari kehangatan keluarga. Awalnya, aku merasakan terjangan traumatis. Bicara di balik masker, air putih yang terasa sepet di tenggorokan, dan makanan yang seperti peluh kardus membuat hari-hariku semakin suram. Berita tentang ribuan kematian akibat virus ini menggerogoti sarafku, merajai ketakutan yang tak kunjung sirna.
Namun, di tengah ansietas itu, percakapan dengan Bapak menjadi pelipur lara. Dia, yang memiliki humor mirip kami anak-anaknya, mengajak kami menelusuri lorong kenangan. Kami tertawa mengingat masa lalu—cerita pendekatannya kepada Ibu, kisah yang kadang terkesan dibuat-buat, namun menambah hangat suasana. Sesekali, aku membacakan puisi buatanku kepada Bapak, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan komentar yang tak terduga. “Kata-kata itu seperti melukis dunia, Nak,” katanya suatu ketika. “Bahasa adalah cara kita menuliskan identitas kita, sekaligus mengenalkan siapa kita kepada dunia.” Itu membuatku merasa lebih dekat lagi dengan beliau, seolah kata-kata yang tertuang dalam puisiku menjadi jembatan untuk lebih memahami perasaan yang sulit terungkapkan.
Setelah 12 hari terkurung dalam ruang isolasi, aku bebas dari gejala lebih dulu. Bapak mengajakku untuk melanjutkan isolasi hingga 14 hari, “Biar genap dua minggu,” katanya. Aku mengikuti anjurannya, dan dua hari berikutnya kami habiskan dengan obrolan tanpa batas, menjelajahi topik yang tak pernah habis.
Suatu waktu Bapak tertawa kecil, lalu berkata dengan nada ringan, “Bahasa itu penting, Nak. Tanpa bahasa, kita bisa kebingungan. Coba bayangkan kalau kita lagi di pasar, terus orang-orang mau jual beli tapi cuma bisa saling pelongo, karena belum ada bahasa yang menghubungkan. Bisa dibayangkan kikuknya kayak apa, kan?” Kami pun tertawa. “Makanya, bapak selalu suka mendengar puisimu. Bahasanya sangat kaya, bapak ingin bisa mengekspresikan diri sebebas dan selepas itu,” katanya saat itu.
Dua Minggu genap, seperti kata Bapak, kami kembali ke rumah. Aku melanjutkan pendidikan daringku, sementara Bapak kembali bekerja demi nafkah. Hari-hari isolasi itu perlahan-lahan terlupakan, seolah hanya menjadi kenangan biasa. Hari demi hari, berbagai varian virus corona seperti omicron dan arcturus datang silih berganti, namun kehidupan kami berjalan kembali. Bapak semakin sibuk, dan aku dikirim ke luar kota untuk mengejar ambisi pendidikan yang sebenarnya merupakan cara untuk melarikan diri dari rumah. Kebutuhan akan kebebasan ini terus menerus mengusikku.
Dengan berakhirnya era covid, sekolah dibuka kembali, begitu pula dengan tempat-tempat umum lainnya. Namun, masih dengan mengikuti prosedur kesehatan untuk berjaga-jaga adanya sisa virus yang masih menjangkit. Komunikasiku dengan keluarga semakin jarang. Di awal Desember, saat orang-orang merencanakan mudik untuk merayakan Natal, aku mengirim pesan untuk minta izin tidak pulang—kataku, ada ujian yang harus dijalani. Sebenarnya, itu adalah kebohongan kecil. Di bulan kelahiranku, aku tahu banyak rencana meriah telah dipersiapkan oleh orang-orang terdekatku. Aku ingin merayakan bersama mereka.
Hari itu, seperti biasa, aku pergi ke sekolah dengan perasaan yang cukup ringan. Namun, segala sesuatu berubah seketika setelah bel tanda waktu berakhirnya pelajaran berbunyi. Salah satu guruku mengirimkan pesan singkat, meminta aku segera menghadap Kepala Yayasan. Aku pikir, mungkin beliau hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mengingat hubungan kami yang begitu dekat dan akrab. Tapi, ketika aku melangkah masuk ke ruang Kepala Yayasan, aku disambut dengan pelukan hangat yang tidak kuharapkan.
Pelukan itu terasa sangat berbeda, seperti ada beban yang berat. Dan saat aku mendengar suara itu, suara yang penuh isak dan duka, aku tahu ada sesuatu yang sangat salah.
Kata-kata yang beliau ucapkan seperti petir yang menyambar tanpa ampun, menghancurkan duniaku dalam sekejap. Jantungku serasa berhenti berdetak, tubuhku lemas, dan segala yang ada di sekelilingku seakan hilang dalam kebisuan. Kenangan-kenangan yang sempat terasa biasa—tawa bersama, cerita-cerita yang dulu sering kami bagi—kini hanya menjadi bayangan yang semakin memudar. Aku terjebak dalam kekosongan yang tak bisa kuterima. Bapak meninggal dunia.
Bapakku, yang selalu tampak kuat dan tak tergoyahkan, ternyata masih terjangkit virus itu. Ketika pertama kali merasakan gejala-gejala yang menandakan sesuatu yang tak beres, dia hanya menganggapnya sebagai hal sepele. “Cuma masuk angin, biasa,” katanya. Tanpa ragu, dia pergi ke warung dekat rumah, membeli obat-obatan yang tak lebih dari sekadar penanganan sementara. Di matanya, pekerjaan dan tanggung jawab untuk keluarga lebih penting dari apa pun.
Meski badannya mulai lemas dan demam tak kunjung reda, Bapak tetap memilih untuk bekerja. Dia tidak ingin kami, anak-anaknya, merasa kesulitan. “Bapak kalau di rumah terus, badan sakit semua. Tipe tulang bapak ini harus dibawa kerja biar nggak kaku,” itu selalu menjadi alasan yang dia utarakan dengan tegas, meskipun dia sudah semakin tampak kelelahan. Setiap hari, ia tetap bekerja di luar ruangan, berhadapan dengan risiko yang semakin membahayakan dirinya. Bahkan ketika kesehatan mulai menurun, Bapak tidak ingin berhenti, tidak ingin kehilangan pekerjaan yang sudah memberikan penghidupan bagi keluarga kami.
Tanpa disadari, virus itu semakin merusak tubuhnya, menyelinap lebih dalam dan lebih dalam, membawanya pada kondisi yang tak terelakkan. Akhirnya, ketika tubuhnya sudah benar-benar tak mampu lagi bertahan, Bapak terpaksa dirawat di tempat perawatan yang disediakan oleh tempat kerjanya. Di sana, dalam keheningan malam yang panjang, tubuh yang tak lagi kuat itu akhirnya menyerah. Virus yang tidak tampak itu merenggutnya dengan cara yang perlahan, mengikis hidupnya sedikit demi sedikit, tanpa kesempatan untuk bertahan lebih lama.
Aku tak pernah membayangkan bahwa keputusan untuk terus bekerja demi keluarga itu, yang dia anggap sebagai kewajiban, justru menjadi alasan terakhirnya meninggalkan kami. Aku merasa begitu hampa. Semuanya terasa begitu tidak adil. Betapa besar cintanya pada kami, sampai dia rela mempertaruhkan nyawanya demi memberikan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, dia pergi juga—karena sebuah pilihan yang tidak pernah bisa kembalikan lagi.
Pikiranku terombang-ambing. Virus yang sempat memisahkan kami secara fisik kini telah mengambilnya dariku—sosok yang paling berarti dalam hidupku. Kehilangan itu datang dengan begitu kejam, merenggut segala yang aku anggap tak tergantikan. Aku merasa terperangkap dalam keheningan yang mencekam, tak bisa berkata-kata, hanya bisa merasakan pedih yang mengiris hati.
Sesampainya di rumah, suasana itu langsung menyambutku—tak ada keceriaan, hanya suasana muram yang menghangatkan hati yang sudah dingin. Rumahku, rumah yang kemarin kutinggalkan untuk mencari kebebasan, kini menjelma rumah duka yang begitu ramai. Tangisan dan bisik-bisik orang-orang memenuhi setiap sudut. Lampu-lampu menyala terang, tapi seakan tak mampu menerangi gelapnya hati yang kini tenggelam dalam kebingungan dan kesedihan.
Tidak ada yang lebih aneh daripada merayakan ulang tahunmu dengan keramaian yang seperti ini. Tak pernah sebelumnya aku merasa ulang tahunku menjadi acara yang begitu riuh, namun begitu kosong. Orang-orang datang, mereka berbicara tentang kenangan, tentang kebaikan Bapak, tentang bagaimana beliau adalah sosok yang luar biasa, tapi aku tak bisa merasakan apapun. Semua itu bagaikan kabut yang menghalangi mataku. Kegembiraan mereka hanya menambah berat beban di pundakku, seolah mereka tak mengerti bahwa kebahagiaan itu tak ada lagi, entah di mana. Bapakku tak lagi ada. Kehilangan ini, begitu mendalam tiba-tiba.
Kehilangan Bapak tanpa diduga—itu seperti dihantam gelombang yang datang begitu cepat, tak memberi kesempatan untuk bernafas atau mempersiapkan diri. Satu hari aku masih mendengar suaranya, merasakan pelukannya yang hangat, dan dalam sekejap, ia menghilang. Kepergiannya membuat dunia seakan berhenti berputar, dan aku terjebak di sebuah ruang yang begitu asing. Bagaimana bisa aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal? Bagaimana bisa hidup terus berjalan sementara aku merasa begitu kosong?
Dalam keadaan seperti itu, akalku mulai kacau. Aku ingin menyalahkan sesuatu, seseorang—apa pun, agar rasa tidak ikhlas ini sedikit reda. Aku mencari-cari oknum yang bisa disalahkan demi menenangkan amarahku yang menggebu. Mengapa Bapak harus pergi begitu cepat? Mengapa virus itu bisa merenggutnya? Bukankah ada banyak orang yang lebih pantas pergi daripada beliau? Aku ingin meluapkan rasa marahku pada dunia, pada takdir yang begitu kejam, pada siapa pun yang bisa menjadi kambing hitam dalam pikiranku yang tak terkendali.
Aku ingin berteriak, ingin berontak, tetapi tak ada yang bisa kugunakan untuk melepaskan semua rasa itu. Dalam kepedihan yang menyesakkan, aku merasa seolah tak ada yang bisa menolong. Ucapan-ucapan penuh penghiburan hanya terasa kosong di telingaku. Dunia mereka berjalan seperti biasa, sementara aku—aku terhenti di sebuah titik yang gelap. Tanpa Bapak, tanpa sosok yang dulu selalu ada, aku merasa hilang, tak tahu lagi bagaimana harus melangkah.
Apa yang tersisa setelah semua ini?
Hanya kekosongan. Ya, kekosongan yang menjeratku tanpa ampun. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku masih percaya ada harapan, ada hidup yang bisa dirajut kembali meskipun di tengah puing-puing. Tapi sekarang, aku tahu betul—kekosongan itu tak akan pernah mengisi apa-apa. Dia hanya ada untuk menghisap segala yang ada, tanpa meninggalkan bekas. Seiring berjalannya waktu, dunia ini terasa seperti hanya hitam putih. Isinya hanya berupa dikotomi yang sifatnya hierarkis dan tidak pernah ada warna-warna lain. Warna-warni itu hanya ilusi!
Kehilangan ini memorak-porandakan segalanya. Semua yang dulu kukenal, yang dulu aku anggap pasti ada, sekarang terasa begitu rapuh. Aku merasa seperti berjalan di atas salju yang mulai mencair—terperangkap di antara kenangan dan kenyataan yang tak bisa kuterima. Tak ada lagi senyum Bapak yang bisa menguatkanku, tak ada lagi obrolan jenakanya yang mampu membuatku merasa aman. Aku hanya punya kekosongan ini, dan rasa marah yang terus membara, tak tahu harus disalurkan ke mana.
Apa yang tersisa? Kosong, tentu saja. Kosong dan kehampaan yang tak bisa diisi dengan apa pun. Aku duduk di sana, menatap dunia yang terbalik, tak ada yang berwarna, tak ada yang indah, hanya reruntuhan—dan aku, berdiri di tengahnya, merasa lega. Rasanya, inilah yang seharusnya kurasakan setelah semua yang telah terjadi. Setelah mendengar suara bising dari senapan milik almarhum kakekku— yang baru pertama kali kugunakan seumur hidup—akhirnya, aku merasa tak perlu lagi berpura-pura bahagia, karena semua itu—semua itu sudah berakhir.
“Bangun.”
“Langit Sena, kan, namamu?”
“Si Penulis kecil kesayangan bapaknya. Berbeda sekali dengan cerita almarhum tentang anaknya yang lucu dan suka membuat puisi. Aku menemukanmu dengan senapan di tangan dan atap kamar yang berlubang karena… pelurumu meleset.”
Aku bangun dari pingsanku, mendengar suara laki-laki asing yang seperti tahu akan segalanya yang sedang kuhadapi. Aku kira ini dunia lain, mungkin mimpi, mungkin semacam ilusi yang muncul karena terlalu lama tenggelam dalam kesedihan dan kehilangan. Mataku masih kabur, tubuhku terasa lemas, dan udara di sekitar terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikat napasku. Namun, setelah aku mengalihkan pandanganku ke sekitar, aku tersadar—aku masih ada di kamarku, di tempat yang sudah terasa begitu sunyi dan asing sejak kepergian Bapak.
Aku menatap laki-laki itu dengan bingung. Dia duduk di pojok ruangan, wajahnya samar tertutup cahaya lampu yang temaram. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya, tapi ada sesuatu yang terasa familiar. Suaranya yang tenang, namun penuh rasa, seperti seorang yang sudah lama mengenal keluarga kami. Perlahan-lahan aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya.
“Siapa kamu?” suaraku serak, seakan tenggorokan ini tak sanggup mengeluarkan kata-kata yang seharusnya. Aku mencoba untuk bangkit, tapi tubuhku menolak, seakan tak ada lagi energi yang tersisa.
Laki-laki itu menghela napas panjang, dan dengan pelan dia berdiri, mendekat. Di tangannya ada secarik kertas yang lusuh, tampak seperti bagian dari surat yang sudah usang.
“Aksara,” katanya, suara beratnya menggema dalam keheningan kamarku. “Aku dulu perawat di tempat kerja Bapakmu. Aku sering mendengar cerita tentangmu dari Bapak, terutama tentang puisi-puisi yang kamu tulis. Tentang bagaimana kamu, anaknya, selalu punya cara untuk mengekspresikan diri lewat kata-kata.”
Aku terdiam. Perawat? Di tempat kerja Bapak? Tempat Bapak bekerja dulu adalah pabrik besar yang jarang orang tahu dengan jelas seluk-beluknya. Bapak, meskipun bekerja keras di sana, tak banyak cerita yang keluar tentang rekan-rekan kerjanya. Tapi mendengar namanya disebut, sesuatu terasa menggerogoti hatiku.
“Bapak… sering menceritakan tentangku?” Aku hampir tidak bisa mempercayai kata-kataku sendiri. Rasa rindu itu datang kembali, menggerogoti hati yang telah lama mati rasa.
Aksara mengangguk perlahan. “Iya. Aku sering mendengar Bapakmu bicara tentang kamu, Sena. Tentang bagaimana kamu selalu menulis, bagaimana dia bangga dengan setiap kata yang kamu rangkai. Bahkan dia bilang, puisi-puisi kamu bisa membuat dunia ini sedikit lebih indah. Bapakmu, dia orang yang sangat mencintai keluarga, meski terkadang dia terlalu keras pada dirinya sendiri.”
Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kenangan tentang Bapak, yang dulu selalu menulis surat-surat kecil untukku, mengajakku membaca puisi-puisi lama, semuanya datang kembali, seolah-olah hidup dalam ingatan yang tersisa.
Aksara melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, “Saat kamu pergi untuk belajar jauh dari rumah, Bapak selalu bicara tentang kamu dengan cara yang penuh harapan. Tapi dia juga cemas, Sena. Dia tahu kamu memilih untuk jauh, tapi dia tak pernah ingin menghalangimu. Dia ingin kamu bisa bebas, mengejar impianmu—meskipun dia sendiri tak bisa.”
Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang sudah lama tertahan. Bapak, yang dulu selalu mendukungku, ternyata selalu memendam kecemasan yang tak pernah kutahu. Aku merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang tak pernah aku pahami, dan kini, setelah semuanya terlambat, aku baru mulai menyadarinya.
“Kenapa kamu ada di sini?” aku bertanya lagi, sedikit bingung. “Apa maksudmu dengan mengatakan… aku menembakkan peluru ke atap?”
Aksara tersenyum pahit, seperti ada kenangan yang tak ingin dia ungkapkan lebih lanjut. “Itu… mungkin hanya cara untuk mengerti perasaanmu saat ini. Aku dengar kamu merasa kosong, Sena. Seperti ada yang hilang, dan kamu mencoba mencari jalan untuk keluar dari rasa itu. Tapi, kita sering kali melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri ketika kita tak tahu bagaimana cara menerima kenyataan.”
Aku merasa semakin bingung, tetapi ada sesuatu dalam suara Aksara yang membuatku merasa lebih tenang. “Jadi… apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu ada di sini sekarang?”
Aksara menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah mencoba menilai kesiapan hatiku untuk menerima kebenaran yang pahit. Dia menghela napas pelan sebelum melanjutkan.
“Aku di sini karena aku ingin kamu tahu, Sena… Bapakmu tidak mati karena kebetulan. Itu bukan hanya masalah penyakit atau nasib. Aku tahu kamu tidak tahu, tapi perusahaan tempat Bapak bekerja—mereka tak memberikan perlindungan yang cukup pada karyawan. Mereka lebih memprioritaskan pekerja-pekerja muda yang masih segar dan sehat badannya, sementara orang-orang yang lebih tua seperti Bapakmu—mereka hanya dianggap sebagai beban.”
Aku terdiam, mencoba memahami kata-kata Aksara, meski rasa sakit itu sudah mulai merasuki dadaku. Aksara melanjutkan dengan suara berat, penuh penyesalan.
“Bapakmu sudah berumur 60 tahun, Sena. Di mata perusahaan, itu berarti dia sudah ‘tua’. Mereka merasa umurnya sudah tidak lama lagi, jadi lebih baik memberi jatah cuti dan perlindungan kepada yang masih muda. Ketika pandemi datang, mereka membiarkan penyebaran virus begitu saja, tak ada langkah nyata untuk melindungi pekerja yang lebih rentan. Padahal, Bapakmu sudah jatuh sakit, dan meski tubuhnya semakin lemah, dia masih dipaksa bekerja. Mereka tak memberi dia waktu untuk beristirahat, bahkan ketika dia mulai terpapar virus. Bapakmu, meskipun sakit, merasa harus tetap bekerja keras, karena dia tahu kita semua bergantung padanya. Tapi perusahaan… mereka tidak peduli.”
Setiap kata Aksara seperti batu besar yang menghantam dadaku. Rasanya sulit untuk memproses kenyataan ini—bahwa Bapak, yang selalu menjadi sosok yang kuat dalam hidupku, ternyata diperlakukan sekejam itu hanya karena usianya. Aku tak pernah tahu betapa besarnya pengorbanan yang dia lakukan, dan kini, setelah semuanya terlambat, aku harus menerima kenyataan bahwa dia tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan ketidakpedulian dari tempat yang seharusnya melindunginya.
“Aksara…” suaraku serak, hampir tak terdengar. “Kenapa kamu baru memberitahuku semua ini sekarang?”
Aksara menundukkan kepala, seolah merasa berat untuk mengungkapkan lebih jauh. “Aku ingin kamu tahu kebenarannya. Bapakmu berjuang dengan segala cara, meski diabaikan. Itu sebabnya aku datang—untuk memberitahumu bahwa dia tidak pergi begitu saja karena kebetulan. Ada banyak hal yang terjadi di belakangnya, hal-hal yang tak bisa kamu lihat sebelumnya.”
Aku terdiam, mencerna semuanya dalam diam. Kepergian Bapak bukan hanya akibat dari penyakit, tetapi juga akibat sistem yang tidak memedulikan orang-orang seperti dia—yang sudah tua, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan dipaksa untuk terus bekerja meski kesehatan mereka semakin menurun. Rasa sakit yang lebih dalam kini datang, bercampur dengan rasa marah yang sulit untuk aku kendalikan.
Aku masih terdiam, tenggelam dalam perasaan yang bercampur aduk. Semua yang baru saja Aksara katakan terasa seperti pukulan bertubi-tubi, menghancurkan segala kenyataan yang kupegang tentang Bapak. Aku ingin marah, ingin mengutuk perusahaan yang begitu kejam, tetapi kata-kata Aksara berikutnya menghentikan semua itu.
“Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan,” Aksara berkata pelan, memecah keheningan yang memadati kamarku. “Bapakmu… sebelum dia pergi, dia sempat berbicara tentangmu. Tentang impianmu, tentang cita-citamu yang masih kamu pegang, meski terkadang terasa jauh dan tak terjangkau.”
Aku menatap Aksara, mataku mulai berkaca-kaca. Dia berjalan mendekat, memegang secarik kertas yang tadi dia bawa, kertas yang tampak sudah usang dan penuh lipatan. Dia menyerahkannya padaku.
“Bapak ingin kamu tahu, Sen,” lanjutnya, suaranya semakin lembut. “Bapak ingin kamu tetap melanjutkan pendidikanmu. Menjadi seorang penulis, itu cita-citamu kan? Kata Bapak, kejarlah. Puisimu—karyamu—bisa jadi inspirasi banyak orang di luar sana. Bapak percaya, kamu punya kekuatan itu.”
Aku terdiam, kata-kata Aksara meresap dalam hati seperti aliran air yang menembus celah-celah batu keras. Kenangan tentang Bapak kembali muncul dalam pikiranku—waktu-waktu ketika dia mengajakku duduk bersama, membaca puisi-puisi lama, dan berbicara tentang dunia sastra yang seakan tak ada habisnya. Kini, aku mulai memahami betapa besar harapan yang dia simpan untukku, meskipun dia tak pernah mengungkapkannya secara langsung.
Aksara melanjutkan, “Bapak ingin kepergiannya tidak sia-sia, Sena. Dia ingin kamu terus berjalan, meskipun dia tak ada lagi di sampingmu. Tolong abadikan dia di karya sastramu. Jadikan setiap kata yang kamu tulis sebagai bentuk penghormatan dan kenangan untuknya. Itu yang dia inginkan dari kamu, Sen.”
Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang perlahan mulai membasahi pipi. Di saat aku merasa begitu kehilangan, Bapak justru meninggalkan pesan yang begitu kuat, sebuah harapan yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Aku tahu, keinginan Bapak itu bukan sekadar tentang puisi atau tulisan. Itu tentang hidupku—tentang aku yang harus terus melangkah maju meskipun dunia terasa gelap dan sepi tanpa kehadirannya.
Aksara berdiri di dekatku, memberi waktu untuk aku mencerna semua ini. “Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan. Kamu punya potensi yang luar biasa. Bapak tahu itu, dan dia ingin kamu mengejar mimpi-mimpimu dengan sepenuh hati. Jangan biarkan rasa kehilangan ini membuatmu berhenti.”
Aku mengangkat kepala, menatap Aksara dengan mata yang masih berkaca-kaca, tapi kali ini, ada sedikit cahaya yang mulai muncul di dalam diriku. Aku merasa seperti baru saja mendapat secercah harapan yang sangat dibutuhkan—sebuah arah untuk melangkah maju.
“Terima kasih,” kataku dengan suara bergetar. “Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku… aku akan melanjutkan pendidikanku. Aku akan menulis, seperti yang Bapak inginkan.”
Aksara tersenyum kecil, wajahnya penuh pengertian. “Aku tahu kamu bisa. Bapak bangga padamu.”
Dengan itu, Aksara berpamitan dan keluar dari kamarku. Aku masih duduk di tempatku, memegang kertas yang tadi dia berikan. Dalam diam, aku merenung. Kata-kata Aksara, serta pesan terakhir dari Bapak, berputar dalam pikiranku. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah—perjalanan hidup, perjuangan, dan penulisan—semuanya terasa begitu berat. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih kuat.
Bapak mungkin telah pergi, namun harapan dan cintanya tetap hidup di dalam diriku. Aku harus melanjutkan apa yang dia percayai. Menulis, untuknya, dan untuk diriku sendiri. Seperti yang dia katakan—aku harus menjadikan puisiku sebagai pengabdian, sebagai penghormatan untuk hidupnya, untuk semua yang telah dia lakukan. Dan, entah seberapa lama perjalanan ini, aku tahu satu hal pasti: aku tidak sendirian.
Perlahan, aku melihat kembali warna-warna itu berkelap-kelip di dalam sinar. Meski malam itu datang, tetapi gelapnya tidak benar-benar menghilangkan warna itu sendiri. Sebuah harapan, seberkas cahaya yang tak pernah padam. Aku merasa seolah-olah Bapak ada di sini, mengawasi langkahku, memberikan kekuatan dari tempat yang tak tampak. Dan benar, kepingan puzzle yang datang entah darimana itu… pasti ada. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang harus aku terima, sebuah petunjuk yang Bapak tinggalkan, yang kini aku harus tuntaskan.
Aku mengecek ponsel, temperatur meningkat 3° Celsius, pertanda matahari mulai naik menghangatkan sebagian dari muka bumi. Namun, ada sesuatu yang lebih hangat dalam hatiku. Sesuatu yang lebih dari sekadar suhu fisik—sebuah rasa yang mengalir, meresap dalam setiap aliran darahku. Aku melipat secarik surat itu, menyimpannya kembali di antara halaman binderku, seolah-olah menjaga setiap kata yang tertulis sebagai warisan yang harus aku jaga. Surat itu adalah jantung dari setiap karya yang akan kutulis—sebuah janji yang takkan pernah aku ingkari.
Aku merenggangkan otot bahu, bersiap melanjutkan sisa-sisa Aksara di dalam novelku yang harus kurampungkan segera untuk diterbitkan tahun ini. Mungkin di bulan Desember. Desember, bulan yang sama di mana Bapak mengajarkan aku bahwa kata-kata bisa hidup selamanya, bahwa cerita tidak hanya milik mereka yang ada di dunia ini, tetapi juga bagi mereka yang telah pergi. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap alur, ada bagian yang abadi—seperti cinta yang tak pernah mati. Dan di setiap halaman yang kutulis, aku tahu aku akan menemukan jejak-jejak Bapak.
Namun, kini lebih dari itu. Aku menulis bukan hanya untuk Bapak, tapi juga untuk bahasa—bahasa yang kami warisi, yang telah menyatukan kami sebagai bangsa. Bahasa yang bukan sekadar rangkaian kata, tetapi jembatan untuk menyampaikan cerita kami, sejarah kami, dan identitas kami. Bapak selalu bilang, “Kata-kata itu bukan hanya alat komunikasi, Nak. Mereka adalah bagian dari siapa kita, dari tanah tempat kita berpijak, dan dari semua yang telah kita lalui sebagai bangsa.”
Satu kalimat itu terngiang kembali dalam pikiranku: bahwa setiap puisiku membuat dunia ini sedikit lebih indah, sedikit lebih mengenal siapa kita. Sebagai bangsa yang besar, yang tak melupakan akar dan bahasa yang telah membentuknya. Aku memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang mengalir deras, dan mengucapkan doa dalam hati. Untuk Bapak. Untuk diriku. Untuk bahasa yang mengikat kita semua, yang akan terus hidup, meskipun waktu terus berjalan.
Aku tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak sendirian. Bapak ada di sini, dalam setiap huruf, dalam setiap kalimat, dalam setiap cerita yang kutulis untuknya. Dan inilah, apa-apa yang tersisa itu—warisan yang harus dijaga, cerita yang harus diteruskan, dan bahasa yang harus kita pertahankan. Begitu cukup rasanya. Terimakasih, Pak.
Selesai.
Biodata Penulis
Nama : Kezia Karen Hapukh Hutagalung
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Desember 2006
Pendidikan : Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan
Penghargaan : Juara 2 Lomba Cipta Cerpen Mahasiswa Se-Sumatera Utara
Pekerjaan : Mahasiswa, penulis lepas
Minat Menulis : Cerpen dengan genre kehidupan, dan puisi-puisi roman
Instagram : @karenlogy
Email : [email protected]