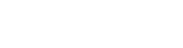Karya: Try Widya Andini
Bruk! Sebuah teko jatuh ke lantai. Minggu pagi Parta sudah sibuk mencari joran miliknya di dapur. Ia berencana pergi memancing bersama Seno, teman sekelasnya di sekolah.
“Kakek, Parta pergi, ya!” katanya menghampiri Kakek Gino setelah berhasil menemukan joran yang dicari-carinya selesai memporak-porandakan dapur. Kakek Gino mengangguk melihat cucunya berlari menjauhi rumah sembari memegang joran dan meninting sebuah ember hitam.
Parta tinggal bersama kakeknya di Desa Cempaka, sebuah desa di pesisir pantai. Kedua orang tuanya tinggal di kota bekerja sebagai buruh pabrik. Karena keduanya bekerja dan takut Parta tidak terurus, Kakek Gino menawarkan agar Parta tinggal bersamanya saja. Kakek Gino merupakan nelayan yang selalu pergi mencari ikan dari sore hingga dini hari. Sehingga waktu siang ia bisa menjaga cucunya itu.
Desa Cempaka adalah tempat yang tenang. Hamparan laut membentang luas di hadapan mereka, dan dulunya hutan mangrove berdiri kokoh di sepanjang garis pantai. Namun, segalanya mulai berubah ketika pohon-pohon bakau mulai ditebangi untuk dijadikan tambak udang dan vila wisata. Laut yang dahulu kaya akan ikan kini semakin surut hasil tangkapannya, membuat para nelayan seperti Kakek Gino semakin kesulitan mencari nafkah.
Parta dan Seno berjalan menyusuri pematang tambak dengan semangat. Mereka ingin memancing di muara yang masih tersisa, tempat ikan-ikan kecil biasanya berkumpul. Setibanya di sana, mereka segera melemparkan kail ke dalam air yang berwarna kecoklatan.
“Kau lihat itu, Seno?” Parta menunjuk ke arah pantai yang mulai ramai dengan pekerja proyek.
Seno mengangguk. “Iya, sebentar lagi di sini pasti berubah. Tidak akan ada lagi tempat kita memancing.”
Parta terdiam. Ia mengingat cerita Kakek Gino tentang masa lalu desa mereka yang asri. Dulu, katanya, desa ini tidak sekering sekarang. Para nelayan selalu pulang dengan ember penuh ikan. Hutan mangrove juga melindungi desa dari abrasi. Tapi sekarang, tambak-tambak udang itu membuat air menjadi keruh, dan ikan-ikan sulit ditemukan.
“Aku rindu masa lalu desa ini,” kata Parta lirih.
“Tapi kita kan belum lahir saat itu,” sahut Seno.
“Iya, tapi cerita kakek membuatku seakan bisa melihatnya.” Parta menatap air yang tenang. “Aku ingin desa kita kembali seperti dulu.”
Mereka kembali diam, menikmati semilir angin yang bertiup. Tak lama, kail Parta bergerak. Dengan cekatan ia menariknya, dan seekor ikan kecil terangkat ke udara.
“Hore! Aku dapat satu!” serunya gembira.
Seno tertawa. “Ayo, kita lihat siapa yang lebih banyak dapat ikan hari ini!”
Mereka kembali fokus pada pancingan mereka. Meski dunia di sekitar mereka perlahan berubah, mereka masih bisa menikmati waktu kecil mereka dengan tawa dan semangat. Namun, jauh di lubuk hati Parta, ia berharap suatu hari nanti ia bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan keindahan Desa Cempaka seperti dulu.
Siang itu, setelah lelah memancing, Parta dan Seno duduk di atas perahu kecil yang ditambatkan di tepi pantai. Mereka mengamati hamparan laut yang membentang luas. Ombak bergulung-gulung lembut di kejauhan, tetapi Parta menyadari bahwa garis pantai tampak lebih sempit dibandingkan dulu.
“Kata kakek, dulu di sini ada banyak pohon bakau,” ujar Parta sambil menunjuk area yang kini dipenuhi tambak udang.
Seno mengangguk. “Iya, aku ingat waktu kecil sering main di antara akar-akar pohon itu. Tapi, sekarang semuanya sudah ditebang.”
Mereka terdiam, memikirkan perubahan yang terjadi di desa mereka. Bagi mereka, tambak udang dan vila-vila baru memang terlihat megah, tetapi apakah benar lebih baik? Semakin hari, banjir semakin sering terjadi, dan pantai terus terkikis.
Sementara itu, di rumah, Kakek Gino duduk di beranda sambil menatap laut. Hatinya gelisah. Ia telah hidup cukup lama untuk mengenali tanda-tanda perubahan alam. Ombak semakin tinggi, angin semakin kencang, dan bau garam di udara lebih tajam dari biasanya. Ia tahu, alam sedang berbicara.
Malam harinya, badai besar menghantam desa. Angin mengamuk, hujan turun deras, dan gelombang tinggi menerjang pantai. Para warga panik, berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang mereka. Tambak udang yang selama ini dianggap menguntungkan justru tak mampu menahan laju air pasang. Air laut menerobos ke pemukiman, menggenangi rumah-rumah penduduk.
“Kakek! Airnya masuk ke rumah!” teriak Parta ketakutan.
“Kita harus keluar sekarang, Nak!” Kakek Gino menarik tangan cucunya.
Di luar, jeritan warga menggema di tengah badai. “Tolong! Rumahku roboh!” seorang ibu berteriak sambil menggendong anaknya yang menangis.
Seno dan keluarganya berjuang menyelamatkan perahu mereka yang nyaris terseret arus. “Ayah! Pegang tali ini kuat-kuat!” teriak Seno, wajahnya basah oleh air hujan dan air mata.
Air semakin naik. Beberapa warga terseret arus, berpegangan pada puing-puing rumah yang hancur. “Parta, ayo cepat! Kita harus ke tempat yang lebih tinggi!” seru Kakek Gino sambil berusaha menavigasi derasnya air yang semakin meninggi.
Parta berlari, tangannya menggenggam erat lengan kakeknya. Dalam kepanikannya, ia melihat sebatang pohon bakau terakhir yang tersisa di pantai masih bertahan di tengah gelombang yang menggila. “Kakek, lihat! Bakau itu masih berdiri!”
Kakek Gino mengangguk dengan mata berkaca-kaca. “Itulah kenapa kita butuh mereka, Nak. Bakau itu yang melindungi kita dulu.”
Saat fajar merekah, Desa Cempaka dalam keadaan porak-poranda. Beberapa rumah rusak parah, tambak-tambak hancur, dan garis pantai semakin terkikis. Warga berdiri terpaku menatap sisa-sisa kehidupan mereka. Suara tangis terdengar dari sudut-sudut desa, sementara yang lain hanya terduduk pasrah, memandang laut dengan kosong.
Kakek Gino berdiri di tengah-tengah mereka, wajahnya yang keriput semakin terlihat tua dalam cahaya pagi. Ia menghela napas berat, lalu berkata dengan suara bergetar, “Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menangisi apa yang telah hilang.”
Kakek Rusdi, seorang nelayan tua, menatap Kakek Gino dengan mata merah. “Apa yang bisa kita lakukan, Gino? Laut semakin ganas. Kita sudah kehilangan begitu banyak.”
“Kita harus menanam kembali bakau,” ujar Kakek Gino tegas. “Pohon-pohon itu satu-satunya yang bisa melindungi kita.”
Beberapa warga saling bertukar pandang. Seno berdiri di samping ayahnya, Pak Joko. “Benarkah, Kek? Bakau bisa melindungi desa kita?” tanyanya penuh rasa ingin tahu.
Kakek Gino mengangguk. “Dulu, ketika aku masih seumurmu, hutan bakau lebat melindungi desa ini. Tapi kita menebangnya demi lahan tambak. Sekarang kita lihat akibatnya.” Suaranya terdengar penuh penyesalan.
Ibu Seno, Bu Rini, menyahut dengan nada sedih, “Aku ingat dulu, desa kita tak pernah separah ini setiap kali badai datang. Tapi menanam kembali bakau… Itu akan butuh waktu lama, Kek.”
Pak Joko akhirnya berdeham dan berkata, “Tapi jika kita tidak mulai sekarang, bencana seperti ini akan terus terjadi. Aku setuju dengan Kakek Gino. Kita harus bertindak.”
Perlahan, satu per satu warga mulai mengangguk. Kesadaran mulai muncul. Mereka tak bisa terus menyalahkan keadaan. Mereka harus berubah.
Hari-hari berlalu, dan kerja keras pun dimulai. Dengan bantuan komunitas lingkungan yang peduli pada desa mereka, warga mulai menanam bibit-bibit bakau di sepanjang garis pantai. Parta, yang bersemangat membantu, sering kali bertanya pada Kakek Gino tentang cara terbaik menanam bakau.
“Kek, bagaimana kalau ombak besar datang dan menghanyutkan bibit-bibit ini?” tanyanya suatu sore saat mereka sedang menanam.
Kakek Gino tersenyum dan menepuk bahunya. “Kita harus sabar, Nak. Bakau butuh waktu untuk tumbuh kuat. Tapi begitu mereka berakar, mereka akan menjadi benteng yang tak mudah digoyahkan. Sama seperti kita, harus tetap berdiri meski diterpa badai.”
Semangat warga semakin berkobar. Bahkan anak-anak kecil ikut membantu, membawa bibit dari satu tempat ke tempat lain. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan desa mulai terlihat berbeda. Bakau-bakau kecil mulai tumbuh, menciptakan harapan baru bagi warga Desa Cempaka.
Universitas Negeri Medan, 8 Maret 2024